Liputan6.com, Jakarta - Laut tak sekadar hamparan air asin. Bagi jutaan nelayan tradisional di Indonesia, laut adalah nadi kehidupan, ruang budaya, dan sumber harga diri. Namun, ruang hidup ini kian terancam.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam forum diskusi bertajuk “Melihat Lebih Dekat Perampasan Ruang Pesisir dan Laut di Indonesia” menyoroti bagaimana praktik perampasan laut—atau yang dikenal dengan istilah ocean grabbing—telah merampas hidup nelayan sejak dekade 1970-an hingga kini.
Dalam ini ditegaskan bahwa marjinalisasi terhadap komunitas nelayan bukan sekadar sejarah kelam, tetapi menjadi luka yang terus menganga. Perampasan ruang laut kini terjadi dalam rupa proyek reklamasi, tambang pasir, hingga alih fungsi wilayah pesisir yang dijustifikasi lewat kebijakan formal.
“Kami menyebutnya coastal and ocean grabbing. Ini adalah bentuk pengambilalihan ruang dan sumber daya laut secara sistematis oleh negara ataupun korporasi, yang seringkali menyingkirkan masyarakat lokal yang selama ini bergantung hidup pada laut,” ujar peneliti LIPI Dedi Supriadi Adhuri, dikutip Selasa (5/8/2025).
Sikap KNTI Terhadap Praktik Grabbing
Praktik grabbing ini dilakukan melalui tata kelola kelautan yang timpang dan tidak partisipatif. Alih-alih menyejahterakan masyarakat, proyek-proyek tersebut justru menghadirkan ketimpangan baru.
Data terbaru dari BPS pada 2024 mencatat ada lebih dari 2,3 juta nelayan aktif dan sekitar 75 juta penduduk pesisir di Indonesia. Namun ironisnya, komunitas pesisir justru menjadi kantong kemiskinan—sebanyak 25% dari mereka hidup dalam garis kemiskinan atau lebih rendah.
“Komunitas nelayan ini bukan sekadar pekerja laut, tapi juga penjaga ekosistem. Mereka menyelamatkan mangrove, menjaga terumbu karang, dan padang lamun. Tapi sekarang justru mereka yang paling terdampak oleh proyek pembangunan yang tak berkeadilan,” ujar Jaring Nusa Kawasan Timur Asmar Exwar.
Selain mengancam mata pencaharian, perampasan laut juga merampas nilai-nilai non-material yang dimiliki masyarakat nelayan. Dalam budaya suku-suku maritim di Indonesia, laut adalah bagian dari identitas sosial-budaya, spiritualitas, dan bahkan harga diri komunitas.
Pendekatan pembangunan yang menekankan pada privatisasi dan pengamanan akses atas ruang laut dinilai telah menafikan pluralitas nilai dan kepentingan masyarakat pesisir.
“Inilah mengapa kita menyaksikan munculnya resistensi di berbagai daerah, dari Bali, Pulau Pari, hingga Kepulauan Kei. Mereka tidak hanya mempertahankan tanah dan laut, tetapi juga mempertahankan eksistensi,” tambah Dedi Supriadi Adhuri.
Contoh Peristiwa Ocean Grabbing
Meluasnya perampasan ruang laut dan pesisir telah melahirkan berbagai gerakan perlawanan dari komunitas nelayan di berbagai penjuru negeri.
Salah satunya adalah gerakan ForBALI, aliansi masyarakat sipil di Bali yang sejak 2014 konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa. Gerakan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari akademisi, seniman, hingga tokoh adat.
Mereka berhasil mengangkat isu perampasan ruang pesisir ke panggung nasional dan memaksa pemerintah meninjau ulang kebijakan reklamasi.
Contoh lain datang dari Pulau Pari, Kepulauan Seribu, di mana warga lokal menggugat korporasi besar yang mengklaim kepemilikan lahan di atas pulau yang telah mereka huni selama bertahun-tahun. Gugatan tersebut akhirnya dimenangkan oleh warga, menjadi preseden penting dalam perjuangan hak atas tanah dan pesisir.
Semua kisah ini menunjukkan bahwa meski terpinggirkan, komunitas nelayan tidak tinggal diam. Dengan berbekal kearifan lokal, solidaritas komunitas, dan dukungan jaringan sipil, mereka menjadi aktor utama dalam menjaga kedaulatan ruang pesisir.
Langkah yang Diambil
Sangat penting untuk meninjau ulang model pembangunan kelautan nasional. Ditekankan bahwa keberlanjutan ekosistem laut tidak akan tercapai tanpa keadilan sosial bagi nelayan kecil.
Salah satu peluang strategis yang diangkat adalah penguatan OECM (Other Effective Conservation Measures) berbasis komunitas. Berdasarkan pemetaan awal, terdapat lebih dari 390 wilayah pesisir di Indonesia yang berpotensi menjadi area konservasi berbasis masyarakat.
Luasnya mencapai lebih dari 10,2 juta hektare dan dikelola secara adat, lokal, atau kolaboratif dengan pemerintah dan swasta.
Pendekatan ini dinilai lebih menjanjikan karena tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Dalam hal ini, desa-desa pesisir dapat memainkan peran penting melalui penguatan kewenangan lokal, asas rekognisi, dan prinsip subsidiaritas.
“Kalau kita bicara ketahanan pangan, laut adalah jantungnya. Nelayan kecil bukan beban negara, mereka adalah penopang bangsa,” tegas Konsorsium Pembaruan Agraria Beni Wijaya.
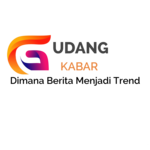
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3292652/original/037078700_1605013125-SKK_migas...jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4026948/original/007431300_1652936420-PLTS-di-sekolah-sebagai-media-pembelajaran-dan-pasokan-listrik-ARBAS-8.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5404433/original/072444000_1762405551-WhatsApp_Image_2025-11-06_at_11.34.42_d7bb0750.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3379589/original/085539600_1613564779-20210217-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-_PEN_-Lewat-Rumah-Bersubsidi-tallo-7.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4826292/original/095830100_1715176226-fotor-ai-20240508204955.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5404267/original/067896300_1762401019-Group_CEO_Hakuhodo_International_Indonesia__Devi_Attamimi-1.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5404279/original/008337400_1762401185-WhatsApp_Image_2025-11-06_at_09.03.27.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5297066/original/050946000_1753669763-Gemini_Generated_Image_4l859a4l859a4l85.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5404218/original/059044900_1762398994-Sekretaris_Jenderal_Kemnaker__Cris_Kuntadi.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5404171/original/002831100_1762396849-fa3d0d36-e0dc-4942-8597-5edfd0add6ad_1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5375986/original/059514000_1759988703-IMG_7642.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5382998/original/053653000_1760612390-2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4805340/original/093907000_1713432001-20240418-Kenaikan_Harga_Emas-HER_2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4066834/original/034753100_1656461868-Harga_Minyak_AFP.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3188318/original/047441700_1595493633-20200723-Usai-Cetak-Rekor_-Harga-Emas-Antam-Kembali-Turun-IQBAL-4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5393451/original/041380100_1761554539-IMG-20251027-WA0005.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1705133/original/008312700_1504951135-ilustrasi_data_center.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310689/original/012718200_1754749069-luca-bravo-TaCk3NspYe0-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5403978/original/093695800_1762346470-WhatsApp_Image_2025-10-28_at_20.30.58_a95b52a3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/976573/original/043185800_1441279137-harga-emas-5.jpg)










:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5316269/original/095179300_1755230967-1000073188.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4103059/original/076150000_1658923818-Harga_emas_menguat_tipis-ANGGA_4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2053635/original/071518800_1522820303-20180404-BI-MER-AB2a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4572281/original/057307700_1694504761-merve-sensoy-UEb7vAqYb4U-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3532289/original/028365400_1628161488-20210805-Harga-emas-alami-penurunan-ANGGA-4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1095897/original/096862700_1451317311-Gedung-PPATK-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5305552/original/006464400_1754356170-IMG-20250805-WA0000.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5252086/original/007300100_1749857885-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303419/original/005458100_1754102666-1000012531.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4592086/original/067091100_1695951584-WhatsApp_Image_2023-09-29_at_8.27.22_AM.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3181749/original/007438500_1594892571-20200716-Rupiah-6.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3431559/original/018558900_1618622607-Ilustrasi_bank_jago_3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5315930/original/011984600_1755179439-4a6f0e71-3a5a-4e3b-ab07-547e802acfa8.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4065432/original/001612500_1656325087-WhatsApp_Image_2022-06-27_at_5.08.03_PM.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5332516/original/077414500_1756509471-1000015044.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4729966/original/074920500_1706586460-taro-ohtani-5T5zmIqs0AM-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5321249/original/062289700_1755667530-IMG-20250820-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3532284/original/011004900_1628161432-20210805-Harga-emas-alami-penurunan-ANGGA-3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5286993/original/074006200_1752805243-d2d1ee03-3c3f-44c2-ad85-75e9d1363e62.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1071006/original/007793200_1448870952-20151130-Harga-Emas-Kembali-Buyback-AY3.jpg)